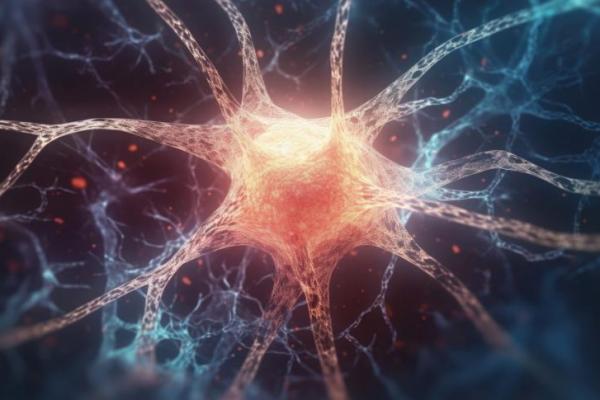Ilustrasi hubungan toxic antara pasangan (Foto: Jeremy Malecki/Unsplash)
Jakarta, Jurnas.com - Banyak orang bertahan dalam hubungan yang jauh di lubuk hati mereka sadari tidak lagi berjalan sehat. Mereka paham bahwa pasangan tidak benar-benar hadir secara emosional, tidak mendukung secara finansial, atau tidak tumbuh bersama dalam relasi. Namun anehnya, kesadaran itu jarang berujung pada keputusan untuk pergi.
Ketika ditanya alasan bertahan, hampir tidak ada yang menjawab karena bahagia. Sebaliknya, yang muncul justru kalimat seperti, “sebenarnya tidak separah itu,” “sudah terlanjur jauh,” atau “takut menyesal kalau pergi”.
Sebenarnya, pola ini bukan sekadar soal cinta, melainkan cara otak manusia memproses kehilangan, risiko, dan perubahan, dikutip dari Psychology Today pada Rabu (28/1).
Cara Aman Bebaskan Diri dari Pasangan yang Toxic
Dari sudut pandang psikologi, bertahan dalam hubungan yang buruk sering kali merupakan respons kognitif yang dapat diprediksi. Ada beberapa mekanisme mental yang bekerja secara halus, namun sangat kuat, sehingga seseorang tetap tinggal meski hubungannya tidak lagi memberi makna.
Berikut tiga alasan utama mengapa seseorang sulit meninggalkan pasangan yang sebenarnya tidak lagi sehat secara emosional maupun relasional.
Alasan pertama ialah kecenderungan menilai pasangan tidak cukup buruk untuk ditinggalkan. Dalam psikologi perilaku, ini dikenal sebagai loss aversion, yaitu kondisi ketika rasa takut kehilangan terasa lebih menyakitkan dibandingkan potensi kebahagiaan yang mungkin diperoleh.
Penelitian tentang prospect theory menunjukkan bahwa manusia jauh lebih termotivasi menghindari kerugian daripada mengejar keuntungan. Dalam konteks hubungan, rasa sakit karena berpisah sering dibayangkan lebih besar daripada kelegaan yang mungkin muncul setelah lepas dari hubungan yang tidak sehat.
Meninggalkan pasangan berarti menerima kehilangan secara langsung, mulai dari waktu yang sudah dihabiskan, rutinitas bersama, identitas sosial, hingga harapan bahwa pasangan suatu hari akan berubah.
Sebaliknya, bertahan berarti mempertahankan sesuatu yang sudah dikenal, meski mengecewakan. Bagi otak, yang familiar sering terasa lebih aman daripada ketidakpastian.
Akibatnya, banyak orang terjebak dalam hubungan yang sekadar cukup layak tetapi tidak benar-benar menyehatkan. Pikiran mereka terlalu fokus pada kerugian yang dihindari, sehingga lupa mengevaluasi apakah hubungan itu masih memenuhi kebutuhan emosional mereka.
Alasan kedua ialah efek sunk cost fallacy, atau jebakan investasi masa lalu. Ini adalah bias kognitif yang membuat seseorang terus bertahan pada sesuatu hanya karena sudah terlanjur mengorbankan banyak hal, bukan karena masih ada manfaat di masa depan.
Dalam hubungan romantis, investasi ini bisa berupa bertahun-tahun kebersamaan, tenaga emosional yang dicurahkan, keterikatan finansial, pengorbanan pribadi, hingga sejarah hidup yang dibangun bersama. Semakin besar investasi itu, semakin sulit untuk melepaskannya.
Mengakhiri hubungan dalam kondisi ini sering terasa seperti mengakui bahwa semua pengorbanan tersebut sia-sia. Secara psikologis, pengakuan semacam itu sangat menyakitkan.
Alasan ketiga ialah ketakutan akan penyesalan di masa depan. Banyak riset menunjukkan bahwa rasa takut menyesal sering lebih kuat daripada harapan akan kepuasan. Dalam hubungan, ini muncul sebagai kekhawatiran bahwa keputusan pergi akan menjadi kesalahan besar.
Seseorang mulai membandingkan hubungan yang sebenarnya tidak sehat dengan skenario terburuk yang dibayangkan, seperti hidup sendiri selamanya, menyadari pasangan lama ternyata adalah pilihan terbaik, atau melihat mantan berubah menjadi lebih baik untuk orang lain.
Perbandingan yang tidak adil ini hampir selalu dimenangkan oleh hubungan yang sedang dijalani, meski kualitasnya rendah. Bertahan terasa seperti cara menghindari penyesalan langsung, sementara pergi berarti harus berdamai dengan pertanyaan “bagaimana jika.”
Dari luar, bertahan dengan pasangan yang tidak berkontribusi sering tampak tidak rasional. Teman atau keluarga bisa dengan mudah menunjukkan ketimpangan dalam hubungan tersebut. Namun kenyataannya, logika jarang cukup kuat untuk mendorong perubahan.
Sebagian besar keputusan manusia tidak digerakkan oleh penalaran sadar, melainkan oleh emosi dan bias kognitif yang bertujuan melindungi diri dari kehilangan dan ketidakpastian. Tanpa mengatasi rasa takut ini, seseorang akan terus merasionalisasi keadaan, menurunkan standar, dan meyakinkan diri bahwa situasi bisa saja lebih buruk.
Memahami mekanisme ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk menghilangkan rasa malu karena merasa terjebak. Bertahan adalah respons manusiawi. Namun perubahan mulai mungkin terjadi ketika fokus bergeser dari investasi masa lalu menuju kesejahteraan di masa depan.
Melepaskan tujuan yang tidak lagi realistis terbukti dapat menurunkan stres dan meningkatkan kesehatan mental. Dalam hubungan, ini berarti menyadari bahwa usaha yang terus dilakukan tidak selalu berujung pada perubahan nyata.
Faktor penting lainnya adalah memisahkan identitas diri dari hubungan. Ketika seseorang kembali terhubung dengan peran, minat, dan nilai di luar pasangan, biaya psikologis untuk pergi menjadi lebih kecil. Hubungan tidak lagi menjadi satu-satunya sumber makna hidup.
Pada akhirnya, meninggalkan hubungan seharusnya tidak selalu dipandang sebagai kegagalan. Secara psikologis, keputusan tersebut lebih tepat dipahami sebagai proses belajar tentang batas diri, kebutuhan emosional, dan arah hidup yang lebih sehat.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
sulit meninggalkan pasangan hubungan tidak sehat psikologi hubungan pasangan toxic