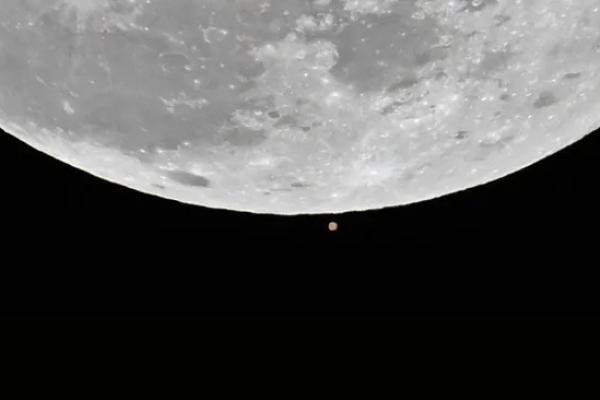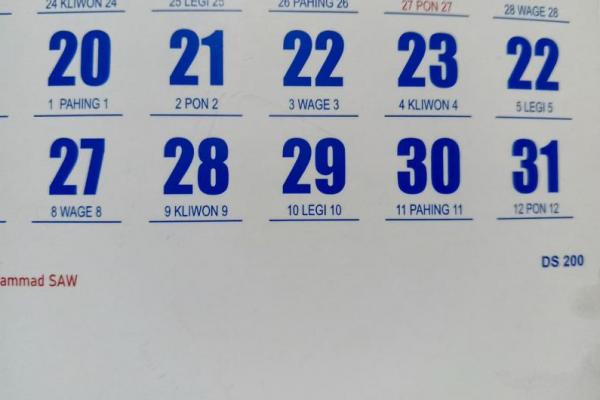Seorang petugas kesehatan dari organisasi Zendai dalam alat pelindung diri (APD) mengambil sampel swab dari seorang gadis untuk tes antigen cepat di tengah wabah penyakit coronavirus (COVID-19), di Bangkok, Thailand, 5 Januari 2022 (Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha)
Jakarta, Jurnas.com - Long COVID masih menjadi teka-teki besar bagi dunia medis. Banyak orang yang tampak pulih dari infeksi COVID-19, tetapi berbulan-bulan kemudian justru mengalami gangguan memori, sulit berkonsentrasi, gangguan tidur, hingga perubahan suasana hati.
Gejala-gejala yang berkaitan dengan otak ini sering kali lebih mengganggu aktivitas sekolah, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari dibandingkan keluhan pernapasan yang tersisa.
Sebuah penelitian internasional terbaru menunjukkan bahwa cara gejala otak akibat Long COVID dilaporkan ternyata sangat berbeda antarnegara, sebagaimana dikutip dari Earth pada Sabtu (31/1).
Perbedaan ini muncul bahkan ketika penyebaran virus terjadi secara global dengan pola yang relatif serupa. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa faktor sosial dan budaya mungkin berperan besar dalam membentuk gambaran Long COVID.
Penelitian ini dilakukan oleh tim Northwestern Medicine yang bekerja sama dengan peneliti di empat negara, yaitu Amerika Serikat, Kolombia, Nigeria, dan India. Lebih dari 3.100 orang dewasa dengan Long COVID dilibatkan, dengan lokasi penelitian di Chicago, Medellín, Lagos, dan Jaipur.
Sebagian besar peserta tidak pernah dirawat di rumah sakit saat pertama kali terinfeksi COVID-19. Meski demikian, mereka terus mengalami gejala neurologis berbulan-bulan setelah dinyatakan sembuh. Salah satu keluhan yang paling sering muncul adalah brain fog, istilah umum untuk kesulitan mengingat, berpikir jernih, dan mempertahankan fokus.
Di Amerika Serikat, sebanyak 86 persen pasien COVID-19 nonrawat inap melaporkan mengalami brain fog. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Kolombia dan Nigeria, yang mencatat sekitar 60 persen pasien dengan keluhan serupa. Di India, hanya sekitar 15 persen pasien yang melaporkan brain fog.
Perbedaan mencolok ini tidak berarti bahwa Long COVID lebih ringan di India atau Nigeria. Varian SARS-CoV-2 menyebar secara global dan tidak menunjukkan perbedaan biologis ekstrem antarwilayah. Para peneliti menilai bahwa faktor sosial, budaya, dan sistem kesehatan jauh lebih mungkin menjelaskan kesenjangan tersebut.
Pola serupa juga terlihat pada gejala gangguan suasana hati. Depresi dan kecemasan dilaporkan jauh lebih sering di negara berpendapatan tinggi. Hampir tiga perempat pasien di Amerika Serikat melaporkan gejala terkait suasana hati, sementara Kolombia berada di tingkat menengah. Di Nigeria dan India, laporan depresi dan kecemasan jauh lebih rendah.
Gangguan tidur mengikuti pola yang sama. Insomnia dialami lebih dari setengah pasien di Amerika Serikat, tetapi jauh lebih jarang dilaporkan di negara lain. Kombinasi temuan ini mengarah pada satu kesimpulan penting: perbedaan kemungkinan besar mencerminkan cara gejala dikenali dan dilaporkan, bukan perbedaan nyata dalam penyakit itu sendiri.
“Di Amerika Serikat dan Kolombia, membicarakan kesehatan mental dan masalah kognitif lebih dapat diterima secara sosial dibandingkan Nigeria dan India,” kata Dr. Igor Koralnik, penulis utama studi ini.
Dia menjelaskan bahwa stigma, kepercayaan budaya, persepsi keagamaan, rendahnya literasi kesehatan, serta keterbatasan layanan kesehatan mental dapat membuat banyak orang enggan atau tidak mampu melaporkan gejala yang mereka alami.
Di masyarakat yang terbuka terhadap diskusi kesehatan mental, keluhan kognitif dan emosional lebih mudah muncul ke permukaan. Sebaliknya, di lingkungan yang masih menstigmatisasi masalah psikologis, tekanan mental sering kali diekspresikan dalam bentuk keluhan fisik seperti nyeri atau kelelahan.
Meski terdapat perbedaan dalam pelaporan, gejala inti Long COVID tetap muncul di semua wilayah. Kelelahan, nyeri otot, pusing, sakit kepala, mati rasa, kesemutan, dan brain fog ditemukan di seluruh negara. Kesamaan ini menunjukkan adanya mekanisme biologis yang sama di balik Long COVID lintas populasi.
Aktivasi sistem imun yang berkepanjangan, peradangan tingkat rendah, serta gangguan pada sistem saraf diduga menjadi pemicu utama gejala otak pada Long COVID. Perilaku virus itu sendiri tidak cukup berbeda antarwilayah untuk menjelaskan variasi pelaporan yang ekstrem.
Hasil tes kognitif objektif juga mendukung temuan tersebut. Gangguan memori dan perhatian terdeteksi di semua negara. Namun, negara berpendapatan tinggi menunjukkan tingkat hasil abnormal yang lebih tinggi, sebagian karena penggunaan alat skrining yang lebih sensitif. Di negara berpendapatan rendah, alat skrining yang lebih sederhana kemungkinan gagal menangkap gangguan kognitif ringan.
Akses layanan kesehatan menjadi faktor penting lainnya. Klinik neurologi, skrining kesehatan mental, dan kunjungan lanjutan lebih mudah diakses di negara maju. Semakin banyak pemeriksaan dilakukan, semakin banyak pula kasus yang terdeteksi. Sebaliknya, keterbatasan akses dapat membuat Long COVID tetap tidak terdiagnosis meski gejalanya ada.
Mayoritas kasus Long COVID di semua negara berasal dari pasien nonrawat inap. Artinya, infeksi awal yang ringan tidak menjamin terbebas dari dampak jangka panjang pada otak. Riwayat rawat inap memang meningkatkan beban gejala, tetapi bukan satu-satunya penentu risiko.
Faktor gender juga berperan. Perempuan mendominasi kelompok nonrawat inap di Amerika Serikat dan Kolombia. Sebaliknya, peserta dari India didominasi laki-laki. Hambatan akses layanan kesehatan bagi perempuan di beberapa wilayah Asia Selatan kemungkinan memengaruhi siapa yang akhirnya datang ke klinik, bukan siapa yang sebenarnya sakit.
Analisis statistik menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Kolombia lebih mirip satu sama lain, sementara Nigeria dan India membentuk kelompok tersendiri. Pola ini lebih selaras dengan tingkat pendapatan dan akses layanan kesehatan dibandingkan letak geografis, memperkuat peran faktor sosial dibandingkan faktor biologis.
Para peneliti memperingatkan bahwa jutaan orang di seluruh dunia mungkin hidup dengan Long COVID tanpa diagnosis atau perawatan memadai. Gejala otak yang tersembunyi tetap menurunkan produktivitas, kemampuan belajar, dan kualitas hidup.
Karena itu, para ahli menyerukan pengembangan alat skrining Long COVID yang lebih sensitif dan disesuaikan secara budaya, serta standar penilaian yang dapat diterapkan lintas negara. Tanpa pendekatan ini, beban Long COVID global berisiko terus diremehkan.
Penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Human Neuroscience.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Long COVID otak dampak long covid brain fog COVID gejala Long COVID