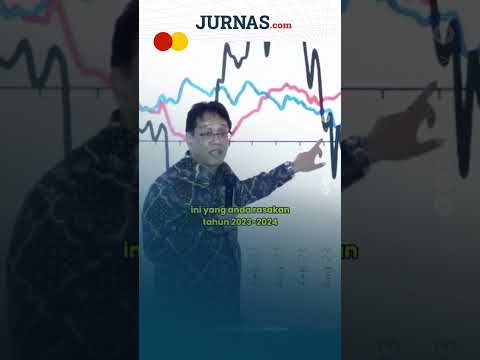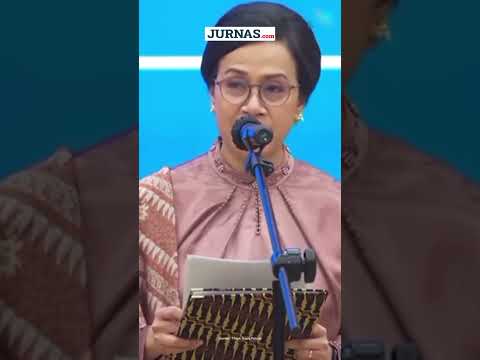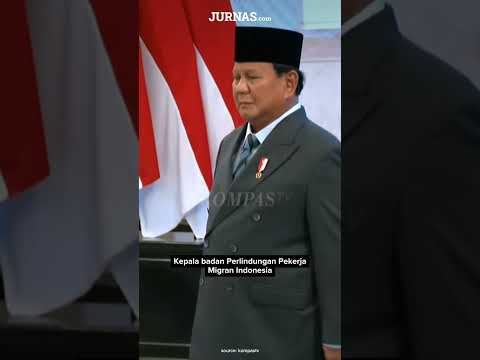Ilustrasi Sejarah Panjang Perjalanan Haji Masa Kolonial Belanda (Foto: abarenumpang/Lmprogress)
Jakarta, Jurnas.com - Sejarah panjang umat Islam di Nusantara atau di Indonesia dalam menunaikan ibadah haji tidak bisa dilepaskan dari tekanan dan pengawasan ketat yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda. Ibadah yang sejatinya sakral dan spiritual ini justru dilihat sebagai potensi subversif yang mengancam stabilitas kekuasaan kolonial. Mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut adalah ulasannya yang dikutip dari berbagai sumber.
Ibadah Haji dalam Bayang-bayang Kolonialisme
Dikutip dari laman Nahdlatul Ulama, jauh sebelum Indonesia merdeka, umat Islam di Nusantara telah menunaikan ibadah haji sejak abad ke-16. Namun, saat kolonialisme Belanda menguat, terutama di bawah kekuasaan VOC dan kemudian Hindia Belanda, ibadah haji justru dianggap sebagai masalah politik dan keamanan.
Menurut M Shaleh Putuhena, penulis buku Historiografi Haji Indonesia, seperti dikutip laman Historia dan Kumparan, disebutkan bahwa VOC sendiri sudah menunjukkan kekhawatirannya sejak abad ke-17. Misalnya, pada 1664, tiga jemaah haji Bugis yang baru pulang dari Mekkah dibuang ke Tanjung Harapan karena dianggap berpotensi menimbulkan kekacauan. Salah satu alasannya, mereka diyakini sebagai pengikut Syekh Yusuf Makassar yang dikenal keras menentang Belanda.
Ketakutan terhadap "efek haji" makin memuncak setelah Perang Diponegoro (1825–1830). Pangeran Diponegoro yang sangat religius memanfaatkan ajaran Islam, termasuk semangat jihad, sebagai basis perjuangannya. Perang ini menelan korban besar: sekitar 15.000 serdadu Belanda tewas, dan sekitar 200.000 warga Jawa meninggal dunia. Sejak itu, Islam dan para haji dipandang sebagai ancaman serius.
Ordonansi dan Resolusi: Cara Kolonial Membatasi
Respon kolonial terhadap fenomena ini melahirkan berbagai regulasi yang represif. Salah satunya adalah Ordonansi Haji 1825 yang menetapkan biaya paspor sangat tinggi (f.110) dan denda besar (f.1.000) bagi jemaah tanpa izin. Tujuannya jelas: membendung arus jamaah haji.
Mengapa Thailand Kebal dari Penjajahan?
Dikutip dari laman Kemenag, regulasi ini terus diperbarui, di antaranya Resolusi tahun 1831 dan Ordonansi Haji tahun 1859. Yang menarik, pada 1859 pemerintah kolonial memperkenalkan “ujian haji” — sebuah sistem verifikasi bagi mereka yang pulang dari Mekkah agar benar-benar bisa menyandang gelar "Haji". Mereka yang lulus akan diberi hak mengenakan pakaian khas haji (jubah, sorban, kopiah putih), yang secara tak langsung memudahkan pengawasan terhadap mereka.
Tak hanya soal pembatasan, pemerintah kolonial juga menjadikan haji sebagai sumber pemasukan. Dikutip dari Jurnal Ilmiah Syariah berjudul "Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah", karya Zainal, pengelolaan haji dibiarkan tidak tertib sebagai strategi agar umat Islam enggan berhaji dan pendapatan kolonial tetap mengalir dari jalur birokrasi berbiaya tinggi.
Ketakutan yang Berlebihan dan Tidak Berdasar
Meskipun pemerintah kolonial beralasan bahwa pembatasan ini dilakukan demi ketertiban dan keamanan, banyak sejarawan melihat kebijakan tersebut sebagai manifestasi dari rasa takut yang berlebihan. Effendi dalam Jurnal TAPIs berjudul "Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah: Studi Pemikiran Snouck Hurgronye" menyebut, ketakutan itu sering tidak berdasarkan data lapangan yang obyektif. Bahkan Snouck Hurgronje — orientalis dan penasihat utama urusan Islam di Hindia Belanda — sendiri menilai bahwa tidak semua jemaah haji berbahaya.
Snouck menyarankan untuk memisahkan antara Islam sebagai agama, hukum, dan politik. Dalam konteks haji, ia menyarankan agar pemerintah melihatnya secara statistik, bukan politis. Ia juga menolak “ujian haji” karena dianggap tidak efektif dan menciderai prinsip kebebasan beragama.
Fenomena "Haji Singapura" dan Jerat Ekonomi
Dikutip dari laman Historia dan Kumparan, kebijakan ketat yang diterapkan pemerintah kolonial menciptakan dampak lanjutan. Banyak jemaah Indonesia hanya sampai Singapura karena tertipu, kehabisan dana, atau tak mendapatkan izin. Namun, mereka tetap membeli sertifikat palsu sebagai “bukti” bahwa telah berhaji — fenomena ini disebut sebagai "Haji Singapura".
Pada 1850 hanya 74 orang dari Nusantara yang menunaikan haji, tetapi pada 1855 melonjak menjadi 1.668 orang — lebih dari separuhnya memilih menetap di Mekkah. Artinya, pembatasan tidak menyurutkan niat umat Islam. Bahkan bisa dikatakan, semakin ditekan, semakin kuat semangat berhaji masyarakat.
Begitu juga, ketika Nusantara jatuh ke penguasa Jepang, setelah pemerintahan Hindia-Belanda. Dikutip dari E-Jounal UIN SUKA berjudul "Histografi Manajemen Haji di Indonesia" karya Muhammad Irfai Muslim, disebutkan bahwa dalam persoalan pengurusan perjalanan ibadah haji, pemerintah Jepang juga tidak jauh berbeda dengan penguasa kolonial Hindia-Belanda.
Pemerintah Jepang sangat khawatir dengan semangat jihad dan juga semangat pan-Islamisme yang dikobarkan para jamaah haji sepulang dari ritual ibadah di Makah.
Kolonialisme Tak Mampu Meredam Spirit Haji
Upaya kolonial membatasi, mengawasi, dan mengontrol ibadah haji menunjukkan bagaimana mereka sangat menyadari kekuatan spiritual sebagai bagian dari kekuatan politik dan sosial. Perjalanan haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga sarana pembelajaran, pertemuan lintas budaya Islam, dan sumber semangat perlawanan.
Tak heran jika pemerintah kolonial terus berusaha menekan gelombang jemaah haji. Namun realitas sejarah menunjukkan sebaliknya — gelombang itu justru semakin besar dan tidak terbendung. (*)
Sejarah Haji Indonesia Haji Nusantara Perjalanan Haji Kolonialisme Pembatasan haji