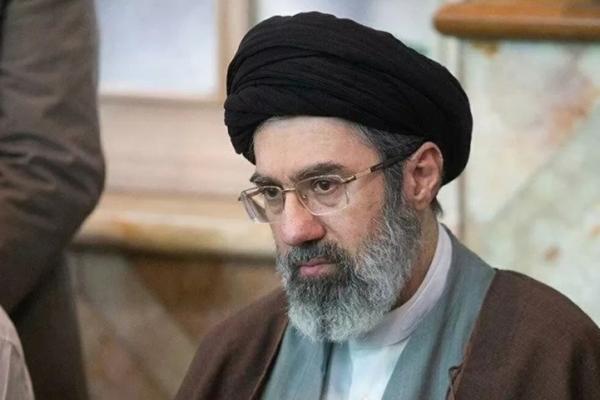Ilustrasi membatalkan janji karena harus beristirahat (Foto: Earth)
Jakarta, Jurnas.com - Hampir semua orang pernah berada dalam situasi merasa bersalah karena terpaksa membatalkan janji makan malam, nonton film, atau sekadar bertemu santai dengan teman.
Adakalanya, mendekati waktu pertemuan, sesuatu yang tidak terduga muncul. Pekerjaan molor, tubuh terasa lelah, atau kepala mulai sakit. Di titik inilah dilema muncul antara memaksakan diri atau membatalkan rencana.
Bagi banyak orang, keputusan untuk membatalkan janji hampir selalu diikuti rasa bersalah. Pikiran tentang mengecewakan teman, terlihat tidak sopan, atau dianggap tidak menghargai waktu orang lain langsung muncul.
Akibatnya, tidak sedikit orang tetap datang meski kondisi fisik atau mental sebenarnya sudah tidak memungkinkan, sebagaimana dikutip dari Earth pada Rabu (21/1).
Penelitian terbaru justru menunjukkan bahwa kecemasan tersebut sebagian besar berasal dari kesalahpahaman. Orang yang membatalkan janji cenderung melebih-lebihkan dampak emosional yang akan dirasakan oleh pihak lain. Dalam kenyataannya, reaksi orang yang dibatalkan jauh lebih ringan daripada yang dibayangkan.
Studi ini mengungkap bahwa sebagian besar orang merespons pembatalan janji dengan sikap yang jauh lebih pengertian. Rasa kecewa memang muncul sesaat, tetapi jarang bertahan lama. Kehidupan tetap berjalan, aktivitas lain menggantikan waktu kosong, dan emosi negatif cepat mereda.
Untuk memahami fenomena ini, para peneliti meminta ribuan partisipan membayangkan berbagai situasi sosial sederhana. Sebagian membayangkan diri mereka membatalkan janji, sementara sebagian lain membayangkan diri mereka sebagai pihak yang dibatalkan. Situasinya mencakup makan malam, konser, hingga pertemuan santai, dengan hubungan yang beragam mulai dari sahabat hingga rekan kerja.
Hasilnya menunjukkan pola yang konsisten. Orang yang membatalkan janji selalu memperkirakan bahwa pihak lain akan merasa jauh lebih terluka dibandingkan kenyataan. Sementara itu, orang yang dibatalkan justru melaporkan bahwa perasaan mereka relatif ringan dan cepat berlalu.
Temuan penting lainnya adalah bahwa sebagian besar orang memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi daripada yang kita bayangkan. Banyak yang menganggap pembatalan sebagai bagian normal dari kehidupan yang tidak selalu bisa diprediksi. Mereka tidak otomatis mengaitkannya dengan kurangnya rasa hormat atau kepedulian.
Penelitian ini juga menyoroti bagaimana pikiran manusia cenderung memperbesar kemungkinan negatif. Pembatalan janji dianggap mampu merusak seluruh hari seseorang, padahal dalam praktiknya, hari tersebut sering kali tetap berjalan normal. Otak lebih fokus pada skenario terburuk daripada hasil yang netral atau bahkan positif.
Selain itu, orang yang membatalkan janji sering merasa perlu “menebus” kesalahan mereka. Mereka membayangkan bahwa pihak lain mengharapkan hadiah mahal, bantuan besar, atau pengorbanan waktu yang signifikan sebagai kompensasi. Padahal, sebagian besar orang hanya mengharapkan permintaan maaf sederhana dan kejujuran.
Dalam penelitian tersebut, para pembatal janji bahkan memperkirakan nilai kompensasi dua kali lebih besar daripada yang sebenarnya diharapkan oleh pihak lain. Pola serupa juga muncul dalam hal waktu dan tenaga, di mana pembatal merasa harus memberikan jauh lebih banyak daripada yang dianggap perlu oleh orang yang dibatalkan.
Para peneliti juga mengamati apa yang terjadi ketika pembatal janji langsung menawarkan pengganti, seperti tiket lain atau rencana pertemuan baru. Tawaran ini memang membantu mengurangi rasa bersalah, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkannya. Bahkan ketika pihak lain sudah terlihat baik-baik saja, rasa tidak nyaman sering tetap bertahan di dalam pikiran pembatal.
Hal ini menunjukkan bahwa sumber utama stres bukan berasal dari situasi itu sendiri, melainkan dari asumsi internal. Orang cenderung terus membayangkan reaksi negatif meskipun bukti nyata menunjukkan sebaliknya. Pikiran inilah yang menjaga rasa cemas tetap hidup tanpa alasan yang kuat.
Penelitian ini mengajak kita untuk memandang ulang arti pembatalan janji. Membatalkan rencana tidak otomatis merusak hubungan. Sebaliknya, komunikasi yang jujur justru lebih dihargai daripada memaksakan diri demi menjaga citra.
Pesan singkat yang jelas, alasan yang masuk akal, serta niat untuk bertemu di lain waktu sering kali sudah terasa cukup. Hadiah besar atau pengorbanan berlebihan jarang benar-benar dibutuhkan. Pemahaman ini dapat membantu mengurangi tekanan sosial yang tidak perlu.
Membatalkan janji juga bukanlah tanda kegagalan sosial. Banyak orang membayangkan bahwa satu pembatalan bisa mengubah cara pandang teman terhadap mereka. Padahal, sebagian besar hubungan tidak ditentukan oleh satu peristiwa kecil seperti itu.
Kehidupan setiap orang dipenuhi dengan kesibukan dan ketidakpastian. Satu rencana yang berubah jarang menjadi penentu kualitas sebuah pertemanan. Yang lebih penting adalah konsistensi, kejujuran, dan rasa saling memahami dalam jangka panjang.
Ketika seseorang berhenti mengandalkan rasa bersalah sebagai kompas sosial, interaksi menjadi lebih ringan dan sehat. Hubungan tidak lagi dibangun di atas ketakutan mengecewakan, melainkan pada kepercayaan bahwa kedua pihak sama-sama manusia dengan keterbatasan.
Studi yang dilakukan oleh peneliti dari Grenoble Ecole de Management dan Norwegian School of Economics ini memperkuat satu kesimpulan penting: membatalkan janji lebih bisa diterima daripada yang selama ini kita kira. Dengan memahami hal ini, kita dapat menjalani hubungan sosial dengan lebih tenang, jujur, dan manusiawi.
Penelitian ini dipublikasikan di jurnal PsyArXiv.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
membatalkan janji psikologi hubungan sosial rasa bersalah