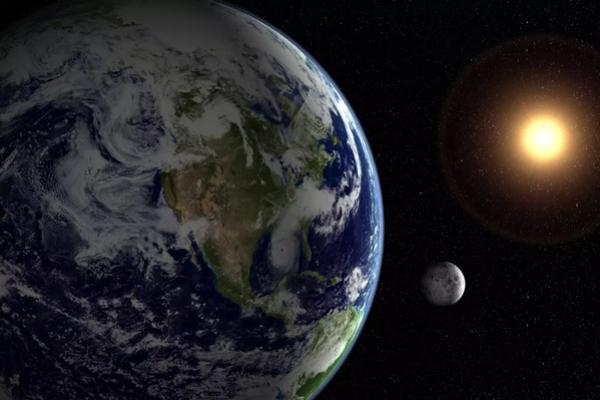Ilustrasi - Pertunjukan di Keraton Yogyakarta (Foto: Mughni/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Kasunanan, Kesultanan, dan Mangkunegaran tercatat dalam sejarah sama-sama lahir dari warisan Mataram yang bergolak sepanjang abad ke-18, namun masing-masing memiliki karakter, legitimasi hingga peran yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya soal gelar penguasa, tetapi juga terkait status politik, otonomi, dan tradisi budaya yang dijalankan.
Secara umum, kasunanan merujuk pada wilayah atau keraton yang dipimpin seorang susuhunan atau sunan, seperti Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sementara kesultanan merujuk pada wilayah yang dipimpin seorang sultan, contohnya Kesultanan Yogyakarta, sedangkan Mangkunegaran adalah kadipaten otonom yang dipimpin Pangeran Adipati Mangkunegoro, memiliki status berbeda dari dua keraton besar.
Sejarah mencatat peristiwa penting “Boyong Kedhaton” pada 1742 ketika Sri Susuhunan Pakubuwana II memindahkan pusat pemerintahan dari Keraton Kartasura yang rusak akibat gejolak politik serta pemberontakan ke Desa Sala di tepi Bengawan Solo. Perpindahan itu menjadi fondasi lahirnya Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang resmi dihuni pada 1743 dan melahirkan konsep baru dari entitas kasunanan ini.
Kasunanan Surakarta atau dikenal Keraton Solo kemudian tumbuh sebagai pusat adat dan budaya Jawa yang menjunjung protokol istana dan menjaga pakem seni klasik. Meski tidak lagi memegang kekuasaan politik secara formal, Surakarta tetap berperan sebagai rujukan utama tata krama dan tradisi Mataram.
Namun ketegangan politik tetap berlangsung hingga akhirnya Perjanjian Giyanti atau Babad Palihan Nagari pada 1755 membelah Mataram menjadi dua kekuasaan besar: Surakarta dan Yogyakarta. Sejak itu, masing-masing keraton menempuh jalur perkembangan berbeda, baik dalam struktur kekuasaan maupun ekspresi budayanya.
Dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono, Kesultanan Yogyakarta memiliki posisi unik, bukan hanya pusat budaya, tetapi juga entitas politik yang berdaulat di tingkat lokal. Sultan Yogyakarta memegang legitimasi politik formal hingga kini, sekaligus menjadi simbol budaya yang menonjol, sehingga keraton ini menempati posisi unik sebagai entitas kerajaan sekaligus pemerintahan modern.
Di sisi lain, munculnya Mangkunegaran beberapa tahun setelah Giyanti menunjukkan bahwa gejolak internal Mataram belum benar-benar usai. Raden Mas Said, tokoh militer yang disegani, menjadi figur penting yang mendorong lahirnya kadipaten ini.
Kedudukannya sebagai kadipaten membuat Mangkunegaran berkembang lebih fleksibel dan progresif dibanding dua keraton besar. Kadipaten Mangkunegaran resmi berdiri pada 17 Maret 1757 setelah Perjanjian Salatiga yang ditandatangani Pakubuwana III dan Raden Mas Said dengan disaksikan perwakilan Yogyakarta dan VOC.
Perjanjian itu memberi K.G.P.A.A. Mangkoenagoro I hak memerintah wilayah luas mulai Kaduang, Nglaroh, Matesih hingga sebagian Pajang yang kemudian memperkuat posisi politiknya.
Mangkunegaran juga memperoleh hak atas pasukan independen yang membedakannya dari kadipaten lain dan menjadikannya kekuatan strategis di Jawa. Dengan kekuatan itu pula Mangkoenagoro I menata kadipaten sebagai pusat budaya dan militer yang inovatif.
Ketika Indonesia merdeka pada 1945, Mangkunegaran di bawah K.G.P.A.A. Mangkoenagoro VIII memilih bergabung dengan Republik dan sempat direncanakan menjadi daerah otonomi khusus bersama Kasunanan Surakarta. Namun revolusi sosial 1945–1946 di Surakarta menghapus kedaulatan itu dan membuat Mangkunegaran kembali fokus sebagai penjaga tradisi.
Ketiga institusi tersebut kini berdiri sebagai pilar budaya Jawa yang saling melengkapi meskipun lahir dari dinamika politik yang sama.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Kasunanan Surakarta Kesultanan Yogyakarta Kadipaten Mangkunegaran Warisan Mataram