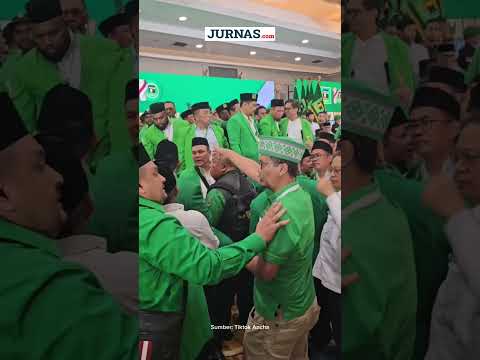Ilustrasi hamparan sawah. (Foto: Wikipedia)
Jakarta, Jurnas.ciom - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 15 Agustus 2025 menandai pergeseran wacana penting dalam politik agraria nasional. Presiden menegaskan kembali Pasal 33 UUD 1945 sebagai "benteng pertahanan ekonomi" yang terabaikan, sambil mengkritik sistem ekonomi yang melahirkan "serakahnomics"—praktik pengejaran keuntungan yang mengorbankan rakyat.
Kritik ini berpijak pada anomali nyata: negara produsen sawit terbesar mengalami kelangkaan minyak goreng, subsidi pertanian mengalir deras namun harga pangan tetap mahal. Di balik anomali ini tersembunyi masalah fundamental: ketimpangan agraria yang tidak tersentuh puluhan tahun. Kini muncul wacana pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria (BPRA). Pertanyaannya: apakah BPRA akan mewujudkan mandat Pasal 33, ataukah mengulangi kegagalan masa lalu?
Ketimpangan Agraria: Akar Krisis Struktural
Data Sensus Pertanian BPS 2023 mengungkap realitas pahit: dari 27,8 juta petani, 17,25 juta (62%) adalah petani gurem dengan lahan kurang dari 0,5 hektare. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 295 kasus konflik agraria sepanjang 2024, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sejak 2009 hingga 2024, terjadi 3.234 konflik melibatkan 7,4 juta hektare dan 1,8 juta kepala keluarga.
Yang lebih mengkhawatirkan bahwa 47,94% penduduk miskin ekstrem yang bekerja ada di sektor pertanian. Ini membuktikan kemiskinan di Indonesia adalah persoalan struktur penguasaan agraria yang timpang, bukan semata produktivitas.
Pemerintah mengklaim telah merealisasikan reforma agraria 14,5 juta hektare. Namun penelusuran lapangan menunjukkan sebagian besar adalah legalisasi asset. Hanya sertifikasi tanah yang sudah dikuasai Masyarakat, bukan redistribusi. Redistribusi di kawasan hutan baru tercapai kurang dari 10%.
Kegagalan ini berakar pada fragmentasi kelembagaan. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk 2016 adalah potret nyata: tidak memiliki kewenangan memaksa kementerian/lembaga, anggaran tersebar di berbagai instansi, dan tidak ada mekanisme penyelesaian konflik yang mengikat. Akibatnya, konflik justru meningkat pasca-pandemi. GTRA membuktikan reforma agraria membutuhkan lebih dari sekdar koordinasi, tetapi ia memerlukan lembaga yang punya kewenagan penuh.
Mendesain BPRA: Belajar dari Kesuksesan Internasional
Taiwan membuktikan efektivitas kelembagaan kuat lewat Sino-American Joint Commission on Rural Reconstruction (JCRR) tahun 1948-1979 yang memiliki kewenangan final dan mengikat. Dari USD 1,5 miliar bantuan AS periode 1951-1965, USD 250 juta dialokasikan khusus pertanian dengan pengelolaan langsung JCRR. Hasilnya: tenancy rate turun dari 38,7% (1948) menjadi mendekati nol, produktivitas beras naik 47%, ekonomi tumbuh 9,21% per tahun.
Korea Selatan melalui Farmland Reform Act (1949) menyelesaikan transformasi dalam 7 tahun. Indonesia era Soekarno pernah memiliki desain serupa: Panitia Pelaksana Landreform dengan Lembaga Pendanaan Landreform dan Pengadilan Landreform. Sayangnya terhenti oleh prahara 1966 sebelum hasil optimal.
Berdasarkan pembelajaran ini, BPRA harus memiliki kedudukan strategis: dibentuk melalui Perpres dengan kedudukan di bawah Presiden setingkat menteri, kelembagaannya tidak permanen, tetapi ad-hoc selama 15 tahun seperti JCRR Taiwan, dengan kewenangan mengeluarkan keputusan mengikat kepada seluruh kementerian/lembaga, BUMN, dan pemda.
Dalam kewenangan operasional, BPRA butuh tiga pilar: Pertama, penetapan objek reforma agraria yang final tanpa gugatan berkepanjangan; Kedua, redistribusi langsung dengan kompensasi jelas mengadopsi model Korea Selatan; Ketiga, penyelesaian konflik melalui mekanisme quasi-yudisial seperti Pengadilan Landreform era Soekarno dengan putusan mengikat, jika tidak dilaksanakan, BPRA berwenang ambil alih aset.
Pendanaan terpusat adalah pembelajaran krusial dari kegagalan GTRA. Mengadopsi model JCRR Taiwan dan Lembaga Pendanaan Landreform Soekarno, BPRA harus mengelola dana khusus dari: retribusi konversi lahan pertanian, dana CSR wajib perusahaan HGU habis/tanah terlantar, dan alokasi khusus APBN, dapat diambil sebagian dari efisiensi Rp.300 triliun yang disebut Presiden berdasarkan Pasal 33 ayat 4.
BPRA juga butuh target terukur dengan akuntabilitas ketat: redistribusi untuk petani gurem dengan timeline jelas, penyelesaian konflik prioritas dalam 3 tahun, dan sanksi tegas termasuk pemberhentian pimpinan jika target tak tercapai. Mekanisme ini yang tidak ada pada GTRA.
Taiwan menyelesaikan transformasi struktural dalam 10 tahun, Korea dalam 7 tahun. Yang dibutuhkan Indonesia adalah keberanian politik mengadopsi pembelajaran ini secara konsisten.
Reforma agraria bukan "program sosial" tapi investasi ekonomi strategis. Taiwan membuktikan: produktivitas pertanian meningkat tajam pasca-land reform, membebaskan tenaga kerja ke manufaktur, menciptakan pasar domestik kuat—double dividend effect. Dengan 17,25 juta petani gurem, reforma agraria berhasil akan menggerakkan ekonomi pedesaan stagnan, menciptakan multiplier effect, dan memperkuat basis ekonomi domestik.
Presiden Prabowo menempatkan kedaulatan pangan dan pemerataan ekonomi sebagai prioritas Asta Cita. Reforma agraria dengan kelembagaan berotoritas penuh adalah kuncinya. Tanpa redistribusi tanah adil, ekonomi pedesaan tetap stagnan, ketimpangan mengakar, kedaulatan pangan hanya jargon kosong.
Pertanyaannya bukan lagi "apakah kita butuh reforma agraria", melainkan: apakah kita punya keberanian politik melaksanakannya sungguh-sungguh—sejalan Pasal 33 yang ditegaskan Presiden Prabowo—agar Asta Cita bukan sekadar janji? Jika BPRA dirancang dengan otoritas memadai, pendanaan terpusat, dan akuntabilitas ketat, Indonesia dapat selesaikan transformasi struktural yang tertunda puluhan tahun. Tetapi jika BPRA hanya jadi GTRA jilid dua—ramai di awal, senyap tanpa hasil—momentum politik akan terbuang sia-sia, dan ketimpangan agraria tetap jadi akar kemiskinan struktural di negeri agraris ini.
Penulis : Idham Arsyad (Ketua Umum GERBANG TANI)
KEYWORD :Prabowo Reforma Agraria BPRA