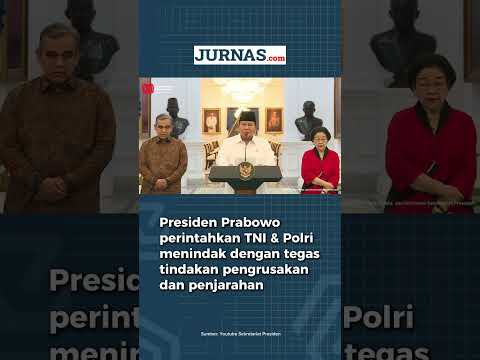Perwakilan gerakan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah menyerahkan dokumen fisik 17+8 tuntutan rakyat yang didominasi warna pink dan hijau ke DPR (Foto: Agus Mughni/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Dalam dunia politik dan protes sosial, warna sering menjadi pesan kolektif. Warna bukan hanya urusan desain atau selera gaya. Dalam sejarah politik dunia, ia telah menjadi bahasa sunyi atau simbol senyap yang mengguncang kekuasaan.
Fenomena ini dikenal sebagai Revolusi Berwarna, gerakan sosial yang menggunakan warna sebagai simbol perlawanan terhadap rezim yang dianggap tidak adil. Tanpa senjata, tanpa kekerasan, tapi cukup kuat untuk memaksa perubahan.
Dikutip dari berbagai sumber, dari Georgia hingga Hong Kong, warna telah digunakan sebagai bentuk ekspresi politik yang sederhana, inklusif, dan sulit ditekan. Ia menyebar dengan cepat, memikat banyak orang, dan mengaburkan batas antara aktivisme dan budaya.
Tahun 2003, rakyat Georgia membawa mawar ke jalanan dan menggulingkan kekuasaan korup dalam Revolusi Mawar. Setahun setelahnya, Ukraina menggelar Revolusi Oranye yang mengubah peta politik nasional mereka.
Iran memiliki Gerakan Hijau, Myanmar punya jubah safron para biksu, Malaysia dengan kuningnya gerakan Bersih, dan Hong Kong memunculkan Revolusi Payung dengan warna kuning sebagai simbol perlindungan dan perlawanan damai. Semua berbicara lewat warna.
Di Argentina, ibu-ibu korban penghilangan paksa mengenakan selendang putih di Plaza de Mayo. Sebuah simbol cinta yang pelan-pelan berubah menjadi ikon keadilan dan perlawanan global.
Menurut Museum of Protest, kekuatan warna terletak pada kesederhanaannya. Semua orang bisa bergabung: cukup mengenakan pakaian, mengikat pita, atau mengganti avatar media sosial.
Pemerintah bisa menyensor slogan, membatasi massa, atau memblokir platform. Tapi warna sulit dilarang—ia terlalu luas, terlalu abstrak, tapi juga terlalu nyata untuk diabaikan.
Kini, gejala serupa terlihat di Indonesia. Sejak akhir Agustus 2025, dua warna mendadak mencolok di ruang digital: Brave Pink dan Hero Green. Simbol itu muncul di avatar, filter TikTok, dan unggahan kreatif hinggga profil media sosial. Dengan cepat, keduanya menjelma menjadi simbol keresahan kolektif yang tersebar luas.
Brave Pink kerap dikaitkan dengan keberanian perempuan, suara-suara terpinggirkan, dan perlawanan terhadap politik maskulin yang beku. Sementara Hero Green dianggap mewakili keresahan generasi muda terhadap krisis lingkungan, korupsi, dan tatanan politik yang stagnan.
Simbol ini tak berdiri sendiri. Ia melahirkan satu bentuk ekspresi baru yang lebih konkret: “17+8”, sebuah paket tuntutan politik dari masyarakat sipil. Angka ini merujuk pada 17 tuntutan utama dan 8 tuntutan tambahan yang disusun oleh jejaring aktivis, mahasiswa, buruh, dan warga sipil. Formatnya ringkas, mudah diingat, dan cepat menyebar sebagai simbol tuntutan yang terukur.
Gelombang ini meletup setelah publik dikejutkan oleh kontroversi kenaikan tunjangan DPR hingga Rp50 juta per bulan. Keputusan itu dianggap menyakitkan, terutama di tengah kondisi sosial ekonomi yang stagnan.
Puncaknya terjadi ketika Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, meninggal dunia dalam bentrokan antara massa aksi dan aparat. Tragedi itu menggetarkan banyak orang dan menyatukan solidaritas lintas kelas sosial.
Dari forum daring hingga diskusi terbuka, lahirlah tuntutan-tuntutan yang mencakup transparansi anggaran, jaminan pendidikan gratis, hingga penghapusan politik dinasti. Sementara delapan poin tambahan menekankan kebutuhan akan reformasi struktural dan transisi ke energi bersih.
Perwakilan gerakan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah secara resmi menyerahkan dokumen fisik tuntutan itu kepada DPR. Aksi simbolis di Gerbang Pancasila disaksikan publik dan diikuti figur publik seperti Jerome Polin, Jovial dan Andovi da Lopez, hingga ekonom muda Andhyta F. Utami.
DPR, melalui Badan Aspirasi Masyarakat, berjanji akan meneruskan dokumen tersebut ke Pimpinan Dewan. Tapi janji politik selalu diuji oleh tindakan, bukan pernyataan.
Sementara itu, sejauh ini gerakan ini nampak tidak punya pemimpin tunggal, tidak ada struktur formal, dan tidak nampak diorkestrasi partai politik mana pun. Tapi di era digital, kekuatan semacam itu justru lebih sulit dikendalikan.
Dalam kerangka teori hubungan internasional, fenomena semacam ini pernah dianalisis oleh John Mearsheimer. Ia menyebut bahwa gerakan rakyat dengan simbol warna sering dimanfaatkan sebagai alat tekanan oleh kekuatan besar—terutama negara-negara Barat.
Contoh paling jelas adalah Ukraina, di mana Revolusi Oranye dan Maidan dianggap sebagai perpanjangan tangan ekspansi pengaruh Barat. Bagi Mearsheimer, ini bukan semata-mata soal demokrasi, tapi soal strategi kekuasaan global.
Lalu, apakah Brave Pink, Hero Green, dan 17+8 juga bagian dari skenario geopolitik? Untuk saat ini, belum terlihat jelas keterlibatan langsung aktor asing—tapi pertanyaan itu tetap layak diajukan.
Karena dalam dunia politik, simbol selalu punya dua wajah: satu untuk moral publik, satu lagi untuk manuver kekuasaan. Dan warna, sering kali berada di tengah-tengahnya.
Namun terlepas dari kemungkinan itu, yang tak bisa diabaikan adalah kenyataan bahwa rakyat Indonesia sedang mencari cara baru untuk bersuara. Mereka muak dengan sistem yang tak berubah dan mulai menciptakan bahasa sendiri untuk menyampaikannya.
Revolusi tidak selalu datang dengan teriakan atau senjata. Kadang, ia hadir dalam bentuk avatar pink, pita hijau, dan barisan angka yang sederhana. Dan seperti sejarah telah membuktikan, perubahan besar sering kali lahir dari simbol yang terlihat kecil—hingga akhirnya terlalu besar untuk diabaikan. (*)
Revolusi berwarna Simbol perlawanan Brave Pink Hero Green Tuntutan rakyat