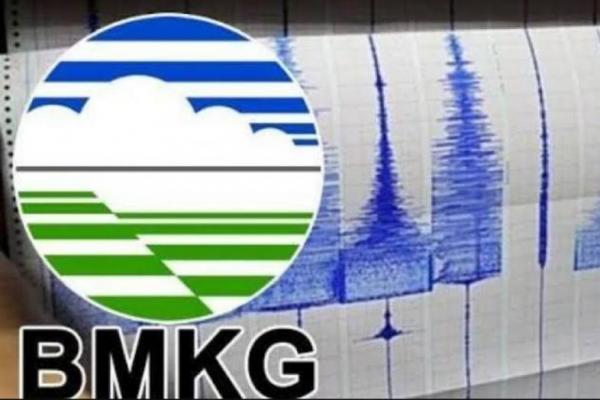Massa mahasiswa menggelar aksi demonstrari di depan Gedung DPR (Foto: Mughni/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Istilah “17+8” mendadak mencuat di berbagai platform media sosial sejak akhir Agustus 2025. Ungkapan ini bukan sekadar deretan angka, melainkan representasi kemarahan kolektif yang berubah menjadi tuntutan politik.
Simbol tersebut merujuk pada 17 tuntutan utama dan 8 tuntutan tambahan yang dirumuskan oleh masyarakat sipil. Format “17+8” dianggap ringkas, mudah diingat, dan cepat menyebar sebagai identitas bersama di tengah gelombang protes nasional.
Gelombang demonstrasi ini bermula dari kontroversi kenaikan tunjangan DPR sekitar Rp50 juta per bulan. Kebijakan itu memicu reaksi keras publik, yang merasa wakil rakyat semakin jauh dari realitas hidup rakyat.
Amarah publik semakin membesar setelah Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, meninggal dunia dalam bentrokan antara aparat dan massa aksi. Tragedi itu mempertegas ketimpangan kekuasaan, sekaligus memicu solidaritas lintas kelas dan generasi.
Dalam suasana krisis kepercayaan, berbagai kelompok mahasiswa, aktivis, buruh, dan warga sipil berkumpul menyusun daftar tuntutan. Dari diskusi daring hingga forum terbuka, lahirlah 17 poin mendesak dan 8 poin struktural sebagai bentuk perlawanan yang terukur.
Tuntutan tersebut menyentuh berbagai aspek kehidupan publik, mulai dari pencabutan tunjangan DPR, transparansi anggaran, hingga jaminan pendidikan dan kesehatan gratis. Sementara delapan poin tambahan menekankan pentingnya reformasi politik, energi bersih, serta penghapusan politik dinasti.
Isu-isu ini dengan cepat menggema di media sosial, diawali dari unggahan aktivis mahasiswa di platform X (dulu Twitter). Dalam waktu singkat, tagar #17plus8 menduduki trending topic nasional dan menyebar ke Instagram, WhatsApp, hingga TikTok.
Breakup Day dan Cara Baru Memaknai Perpisahan
Respons publik begitu masif karena gerakan ini dianggap mewakili keresahan yang telah lama terpendam. Poster digital, mural jalanan, hingga spanduk-spanduk bertuliskan “17+8” mulai bermunculan di berbagai kota sebagai ekspresi perlawanan damai.
Partai-partai politik pun tak bisa mengabaikan tekanan yang muncul dari akar rumput. NasDem dan PAN mengambil langkah cepat dengan menonaktifkan beberapa kader DPR mereka yang menjadi sorotan publik.
Sementara itu, PDIP dan PKB menyatakan dukungan atas aspirasi rakyat, namun menekankan pentingnya menempuh jalur konstitusional. Di sisi lain, Gerindra sebagai partai pemerintah menyampaikan komitmen Presiden Prabowo untuk membatalkan kenaikan tunjangan DPR.
Meski begitu, pemerintah juga memperingatkan agar aksi-aksi yang berlangsung tetap berjalan tanpa kekerasan. Imbauan itu datang di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan eskalasi massa di berbagai daerah.
Di tengah riuh respons elite, masyarakat justru semakin memegang erat simbol “17+8” sebagai penanda identitas kolektif. Banyak warga mengubah foto profil mereka, menggambar mural, hingga mencetak kaus dengan angka tersebut.
Simbol ini menjadi bentuk kritik sekaligus harapan akan hadirnya tatanan yang lebih adil dan manusiawi. Pengamat politik menyebut “17+8” sebagai potensi lahirnya gerakan reformasi baru, seperti halnya yang terjadi pada 1998.
Bedanya, kali ini perlawanan tidak hanya berlangsung di jalanan, tapi juga tumbuh melalui ruang digital yang sangat cepat menyebar. Efeknya bukan hanya nasional, tetapi juga mengundang perhatian dunia internasional terhadap dinamika demokrasi Indonesia.
Gerakan ini tak lahir dari satu tokoh atau partai, melainkan dari kekecewaan kolektif yang menemukan bentuknya dalam angka sederhana. Ia bukan sekadar tren sesaat, tetapi bisa menjadi babak awal dari pergeseran relasi antara rakyat dan penguasa.
Tinggal bagaimana negara meresponsnya—apakah memilih mendengar dan berubah, atau justru menutup telinga dan menambah jarak. Karena di balik angka “17+8”, ada suara rakyat yang tak lagi bisa diabaikan. (*)
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Viral 17+8 Tuntutan Rakyat Media Sosial Simbol