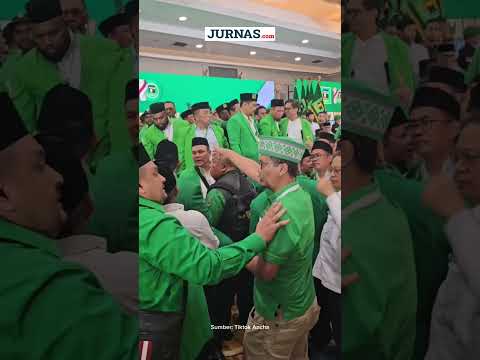Ilustrasi Pajak (Foto: Antara)
Jakarta, Jurnas.com - Aksi ribuan warga di Pati yang memadati jalanan pada 13 Agustus 2025 bukan hanya soal angka kenaikan pajak. Di balik teriakan dan spanduk penolakan hingga tuntutan pengunduran diri, sejarah panjang perlawanan terhadap pungutan yang dianggap tak adil kembali hidup.
Kebijakan Bupati Pati, Sudewo, untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu gejolak luar biasa. Bukan hanya karena lonjakannya yang drastis, tetapi ditengarai karena cara penyampaiannya yang dianggap merendahkan dan menantang.
Pernyataan Sudewo dalam video yang viral pada awal Agustus 2025, “Jangankan 5.000, 50.000 massa silakan… saya tidak gentar!” menjadi pemicu kemarahan warga yang sudah merasa terbebani. Tak lama kemudian, protes pun berubah menjadi desakan politik: pembatalan kebijakan dan pengunduran diri Bupati.
Namun ini diyakini bukan kali pertama rakyat Pati berdiri menentang pajak yang dianggap menindas. Dikutip dari berbagai sumber, sejak abad ke-16, masyarakat di wilayah ini telah terbiasa menyuarakan penolakan terhadap sistem yang mencabut hak hidup mereka.
Pada masa Kerajaan Demak, pajak hasil bumi dinaikkan sekitar 30 persen, membuat rakyat menderita kelaparan dan anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Pemerintah kala itu merespons protes dengan kekerasan, namun perlawanan tetap bergema.
Ketika kekuasaan beralih ke Kerajaan Pajang, masyarakat Pati menolak setoran pajak yang naik 20 persen dan memilih mengalihkan kesetiaan kepada Ki Penjawi. Ini bukan hanya bentuk pembangkangan ekonomi, tapi juga manuver politik rakyat kecil yang tak mau tunduk begitu saja.
Pada era Mataram di bawah Sultan Agung, pajak beras dinaikkan secara sepihak hingga 40 persen. Adipati Pragola I memimpin penolakan, menunjukkan bahwa pemimpin lokal pun bisa berpihak pada rakyat. Adipati Pragola I tercatat sebagai pemimpin Pati yang memberontak Panembahan Senopati, pemimpin Kerajaan Mataram Islam pada 1600-an.
Pemberontakan besar pecah pada 1627 hingga 1628 ketika Pragola II menolak menaikkan upeti sebesar 50 persen. Peristiwa ini berakhir dengan pertumpahan darah, namun juga mengukuhkan Pati sebagai wilayah yang tak mudah ditundukkan.
Konflik kembali muncul saat Amangkurat I menaikkan pajak sebesar 35 persen, dan masyarakat Pati di bawah kepemimpinan Pragola III menolak dengan tegas. Kejadian ini semakin menegaskan sikap konsisten rakyat Pati dalam menolak ketidakadilan fiskal dari pusat kekuasaan.
Saat VOC masuk ke Jawa, tekanan beralih ke pajak perdagangan. Kenaikan bea hingga 25 persen memicu perlawanan yang dipimpin pengikut Sunan Kuning, yang kemudian berlanjut dalam serangan pos-pos VOC pada masa Geger Pecinan.
Untung Surapati turut menjadi simbol perlawanan ketika pajak pelabuhan dinaikkan hingga 40 persen. Di Pati, rakyat ikut mengangkat senjata sebagai bentuk solidaritas terhadap penderitaan kolektif akibat tekanan ekonomi kolonial.
Masuk ke abad ke-19, pajak tanah menjadi instrumen utama penjajahan. Di bawah Daendels dan Raffles, tarif sewa tanah naik 30 persen, memicu penolakan dari tokoh lokal seperti Ki Kromo Pati.
Ketika Cultuurstelsel diterapkan, petani dipaksa menyerahkan 66 persen hasil panen mereka dalam bentuk tanam paksa. Di Pati, mogok tanam menjadi bentuk perlawanan yang paling efektif untuk melawan penghisapan ekonomi itu.
Perjuangan dilanjutkan oleh Ki Samin Surosentiko, yang menolak membayar pajak apapun kepada pemerintah kolonial. Gerakan Samin berkembang sebagai bentuk perlawanan damai dan menjadi inspirasi nasional.
Pada masa pendudukan Jepang, bentuk pajak bergeser menjadi tenaga paksa atau romusha selama 60 hari per tahun. Penderitaan ini memperdalam trauma kolektif rakyat Pati terhadap sistem pajak yang merampas tenaga dan martabat.
Tak berhenti di sana, saat Belanda kembali dalam Agresi Militer II, rakyat Pati menolak setoran pangan darurat yang naik 20 persen. Bagi mereka, tak ada tempat lagi untuk penjajah, terlebih yang masih meminta upeti dalam situasi perang.
Orde Baru juga menyisakan luka. Pada 1965–1966, pajak hasil panen dinaikkan 15 persen, dan rakyat Pati memprotes kebijakan yang dianggap mengabaikan nasib wong cilik.
Reformasi 1998 membawa harapan, namun tak lepas dari masalah. Pungutan liar yang menyedot hingga 10 persen dari harga jual panen membuat aktivis dan petani kembali bersatu menuntut keadilan dan transparansi.
Kini, pada 2025, sejarah tampaknya kembali berulang — tapi dengan angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenaikan 250 persen pada PBB-P2 menjadikannya kenaikan pajak yang dianggap paling gila dalam sejarah Pati, bahkan melebihi masa penjajahan Belanda dan Jepang.
Meski Bupati Pati telah meminta maaf dan membatalkan kebijakan kenaikan pajak tersebut, demonstrasi besar-besaran tidak bisa dibendung. Dalam konteks ini rakyat dinilai tak hanya menolak nominal, tapi juga cara pemerintah daerah memperlakukan mereka seolah tidak punya suara. Demonstrasi pun meluas menjadi isu legitimasi kepemimpinan. DPRD Kabupaten Pati akhirnya diberitakan membuka pintu penggunaan hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan. (*)
KEYWORD :Pajak Pati Kenaikan PBB Sejarah Penolakan pajak Demonstrasi